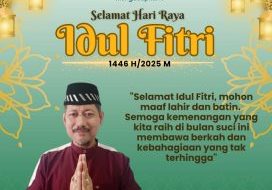(Dr. Tiomy B Adi Unaim Yapis Wamena)
Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April menjadi momen refleksi bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya perempuan, untuk mengingat kembali semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Sosok Kartini bukan sekadar simbol, tetapi pelopor emansipasi perempuan yang membuka jalan bagi kesetaraan pendidikan dan hak-hak perempuan. Namun, perjuangan Kartini tidak berhenti di Jepara. Di tanah Papua, api semangat itu menyala dalam rupa yang berbeda dengan latar belakang budaya, tantangan, dan harapan yang unik. R.A. Kartini lahir dalam tradisi Jawa yang kuat dan patriarkal. Ia mengalami langsung keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan. Namun, lewat surat-suratnya yang kelak dibukukan dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini mengungkapkan pemikiran visioner tentang pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Ia tidak menolak budaya Jawa, tetapi ingin agar perempuan memiliki ruang untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Semangat ini kini menjadi warisan yang diperjuangkan di berbagai pelosok negeri termasuk di Papua.
Perempuan Papua, Antara Tradisi dan Perjuangan Modern
 Perempuan Papua hidup dalam realitas yang berbeda, namun tidak kalah kompleks. Dalam masyarakat adat Papua, perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terutama dalam pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, mereka juga menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan minimnya representasi dalam ranah politik dan pemerintahan.
Perempuan Papua hidup dalam realitas yang berbeda, namun tidak kalah kompleks. Dalam masyarakat adat Papua, perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terutama dalam pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, mereka juga menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan minimnya representasi dalam ranah politik dan pemerintahan.
Di balik tantangan itu, lahirlah banyak “Kartini Papua” yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di tanahnya. Nama-nama seperti Mama Yosepha Alomang, pejuang lingkungan dan hak adat, serta Adriana Elisabeth, aktivis pendidikan, menjadi contoh nyata bagaimana perempuan Papua berjuang dalam diam dan dalam sorotan. Salah satu persoalan paling krusial bagi perempuan Papua adalah akses pendidikan. Banyak anak perempuan di pedalaman Papua yang terpaksa menikah muda karena tidak memiliki pilihan lain. Di sinilah peran perempuan-perempuan pejuang menjadi penting: membangun sekolah alternatif, mengajar secara sukarela, dan memberi penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan perempuan.Dalam konteks ini, semangat Kartini menjelma dalam perjuangan lokal yang kontekstual bukan sekadar mengenakan kebaya, tetapi melawan keterbatasan dengan aksi nyata.
Emansipasi dalam Makna Papua
Emansipasi perempuan seringkali dimaknai sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Bagi perempuan Papua, emansipasi bukan sekadar perjuangan gender, melainkan juga perjuangan melawan ketertinggalan, diskriminasi, dan marginalisasi yang berlapis. Perempuan Papua menghadapi tantangan ganda, yaitu sebagai perempuan dan sebagai bagian dari kelompok yang seringkali termarjinalkan dalam pembangunan nasional. Menurut Martha Nussbaum, seorang filsuf feminis, emansipasi perempuan harus dilihat dari kemampuan perempuan untuk mengakses “capabilities” (kemampuan dasar) seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik.
Dalam konteks Papua, banyak perempuan masih kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas atau terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas maupun politik. Sementara itu, Sara Ahmed, dalam bukunya ‘Feminist Theory, menekankan bahwa emansipasi harus memperhatikan konteks budaya dan struktural. Bagi perempuan Papua, budaya patriarki yang kuat dan dampak konflik berkepanjangan menjadi penghambat besar. Namun, banyak perempuan Papua telah menjadi agen perubahan, seperti terlihat dalam peran mereka sebagai aktivis, guru, atau penggerak ekonomi lokal.
Al-Qur’an secara tegas mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan derajat manusia, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 71)
Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara dalam membangun kebaikan. Selain itu, QS. Al-Hujurat: 13, juga menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah bukan berdasarkan gender, melainkan ketakwaan.
Di Papua, emansipasi perempuan dapat dilihat dari upaya peningkatan pendidikan, seperti program beasiswa bagi anak perempuan Papua, atau gerakan perempuan adat yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan. Namun, tantangan seperti stereotip, minimnya infrastruktur pendidikan, dan dampak kekerasan struktural masih menghambat kemajuan. Di sinilah nilai-nilai Islam tentang keadilan dan pemberdayaan dapat menjadi landasan moral untuk mendukung emansipasi perempuan Papua tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya mereka.
Kebaya dan Noken dalam Narasi Perempuan Indonesia
Dua bahan dari benang yang berbeda, dua budaya yang berjauhan, tetapi sama-sama menjadi simbol kekuatan perempuan Indonesia. Kebaya, pakaian tradisional yang dikenakan R.A. Kartini, melambangkan perjuangan emansipasi dan intelektualitas perempuan Nusantara. Sementara noken, tas rajutan khas Papua yang dibuat oleh perempuan suku-suku Pegunungan Tengah, mencerminkan ketahanan, kebersamaan, dan identitas budaya yang tak tergantikan. Meski berasal dari dunia yang berbeda, kebaya dan noken sama-sama bercerita tentang bagaimana perempuan Indonesia mempertahankan martabat, tradisi, dan hak-haknya di tengah perubahan zaman. Kebaya tidak sekadar pakaian, ia adalah pernyataan politik. Di masa kolonial, kebaya yang dikenakan Kartini menjadi simbol perlawanan halus terhadap dominasi budaya Barat.
Sementara perempuan Eropa mengenakan korset dan gaun ketat, Kartini memilih kebaya sebagai bentuk penegasan identitas. Kebaya juga melambangkan perjuangan pendidikan perempuan. Kartini, yang kerap digambarkan mengenakan kebaya dengan sanggul rapi, menggunakan citra ini untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa elegan sekaligus terpelajar. Ia menolak anggapan bahwa perempuan hanya pantas di rumah; dengan kebayanya, ia membuktikan bahwa perempuan bisa berpendidikan tanpa kehilangan akar budayanya. Kini, kebaya telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda, bukan hanya sebagai pakaian tradisional, tetapi juga sebagai simbol pergerakan perempuan Indonesia.
Noken, Tas yang Menyatukan Perempuan Papua
Sementara kebaya melambangkan intelektualitas, noken tas anyaman dari serat kayu atau anggrek hutan mewakili ketahanan dan kebersamaan perempuan Papua. Dibuat dengan teknik turun-temurun, noken bukan sekadar tas, melainkan simbol kehidupan. Noken dipikul di kepala, menunjukkan kekuatan fisik dan ketabahan perempuan Papua yang menjalani hidup di medan berat. Dianyam dengan kesabaran, mencerminkan nilai-nilai perdamaian dan ketekunan. Digunakan untuk membawa hasil bumi, bayi, atau barang berharga, menjadi tanda kasih sayang dan tanggung jawab. Pada 2012, UNESCO juga mengakui noken sebagai Warisan Budaya Dunia yang Membutuhkan Perlindungan Mendesak. Pengakuan ini muncul karena pembuatan noken terancam oleh modernisasi dan konflik di Papua. Bagi perempuan Papua, mempertahankan noken sama dengan mempertahankan identitas mereka di tengah tekanan sosial dan politik.
Pertemuan Dua Simbol, Kebaya dan Noken dalam Narasi Perempuan Indonesia
Jika kebaya berbicara tentang emansipasi melalui pendidikan, noken bercerita tentang ketahanan melalui kearifan lokal. Keduanya adalah bentuk perlawanan, Kartini dalam kebayanya melawan feodalisme dan kolonialisme dengan pena. Perempuan Papua dengan nokennya melawan marginalisasi dengan menjaga tradisi.
Di era sekarang, kebaya dan noken bisa menjadi simbol persatuan. Ketika perempuan Jawa mengenakan kebaya dengan bangga, dan perempuan Papua tetap menganyam noken dengan tekun, keduanya sedang mengatakan, perempuan Indonesia beragam, tetapi sama-sama kuat. Baik kebaya maupun noken adalah warisan yang harus dilestarikan, bukan hanya sebagai benda budaya, tetapi sebagai simbol perjuangan perempuan Indonesia. Kebaya mengingatkan kita pada pentingnya pendidikan dan kesetaraan. Noken mengajarkan kita tentang ketahanan dan pelestarian tradisi di tengah tantangan. Perjuangan perempuan Papua bukan sekadar mengejar kesetaraan ala barat, tetapi mempertahankan identitas budaya sembari menuntut keadilan sosial. Mereka berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk komunitasnya. Mereka menjadi guru, petani, pemimpin adat, bahkan aktivis yang berani bersuara di forum-forum nasional dan internasional. Emansipasi dalam perspektif Papua adalah menyuarakan hak atas tanah, pendidikan yang layak, kesehatan ibu dan anak, serta keadilan dalam pembangunan.
Kartini Dari Timur” Suara Perempuan Papua Dalam Sunyi”
Di Jawa, Kartini menulis surat dalam kesunyian kamar, melawan batas-batas tak kasat mata yang dibangun oleh adat dan tata krama bangsawan. Ia tidak menggugat dengan suara lantang, tapi dengan pena yang menembus zaman. Surat-surat itu kini menjadi nyala obor yang menuntun ribuan perempuan Indonesia menuju terang.
Namun, jauh di timur nusantara di tanah Papua perempuan juga berjuang. Tidak dengan surat, tapi dengan langkah kaki yang menempuh hutan untuk mengajar, dengan tangan kasar yang mengolah tanah, dan dengan suara yang tak jarang diredam. Mereka tidak menulis dalam bahasa Belanda, tapi dalam bahasa perjuangan, bertahan dan membangun di tengah keterbatasan. Mereka adalah Kartini dari Papua., Mama Yosepha Alomang bukan aktivis yang lahir dari bangku universitas. Ia lahir dari tanah, dari luka panjang yang ditinggalkan tambang dan penjajahan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kampungnya di Amungme dihancurkan, bagaimana alam yang suci bagi masyarakat adat berubah menjadi kolam limbah. Sebagai perempuan adat, Mama Yosepha memimpin dengan kelembutan dan keteguhan. Ia ditangkap, disiksa, dan dipenjara karena berani bersuara. Tapi ia tidak gentar. “Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tidak mau diam. Dalam sosok Mama Yosepha, kita melihat Kartini yang berselendang noken. Kartini yang tidak menulis surat ke Belanda, tapi menuliskan sejarah lewat keberanian.
Pendekar Sunyi di Pegunungan
Di distrik-distrik terpencil Papua, perempuan menjadi penjaga peradaban. Ada mama-mama yang dengan sabar membuka kelas darurat di honai, mengajari anak-anak membaca, menghitung, dan mengenal dunia di balik lembah. Mereka bukan guru bersertifikat, tapi mereka mengajarkan hidup. Seorang perempuan bernama Maria, misalnya, memilih tidak menikah agar bisa mengabdikan hidupnya untuk sekolah rakyat di Yahukimo. Dengan sepeda motor pinjaman dan buku-buku bekas, ia melintasi bukit dan sungai untuk menjumpai anak-anak yang sering terlupakan negara.
Ia tidak pernah tampil di layar televisi atau menerima penghargaan nasional. Tapi di mata anak-anak Papua, ia adalah guru, ibu, dan pahlawan. Seperti Kartini, ia tahu bahwa pendidikan bukan soal bangku dan ijazah tetapi tentang harapan.